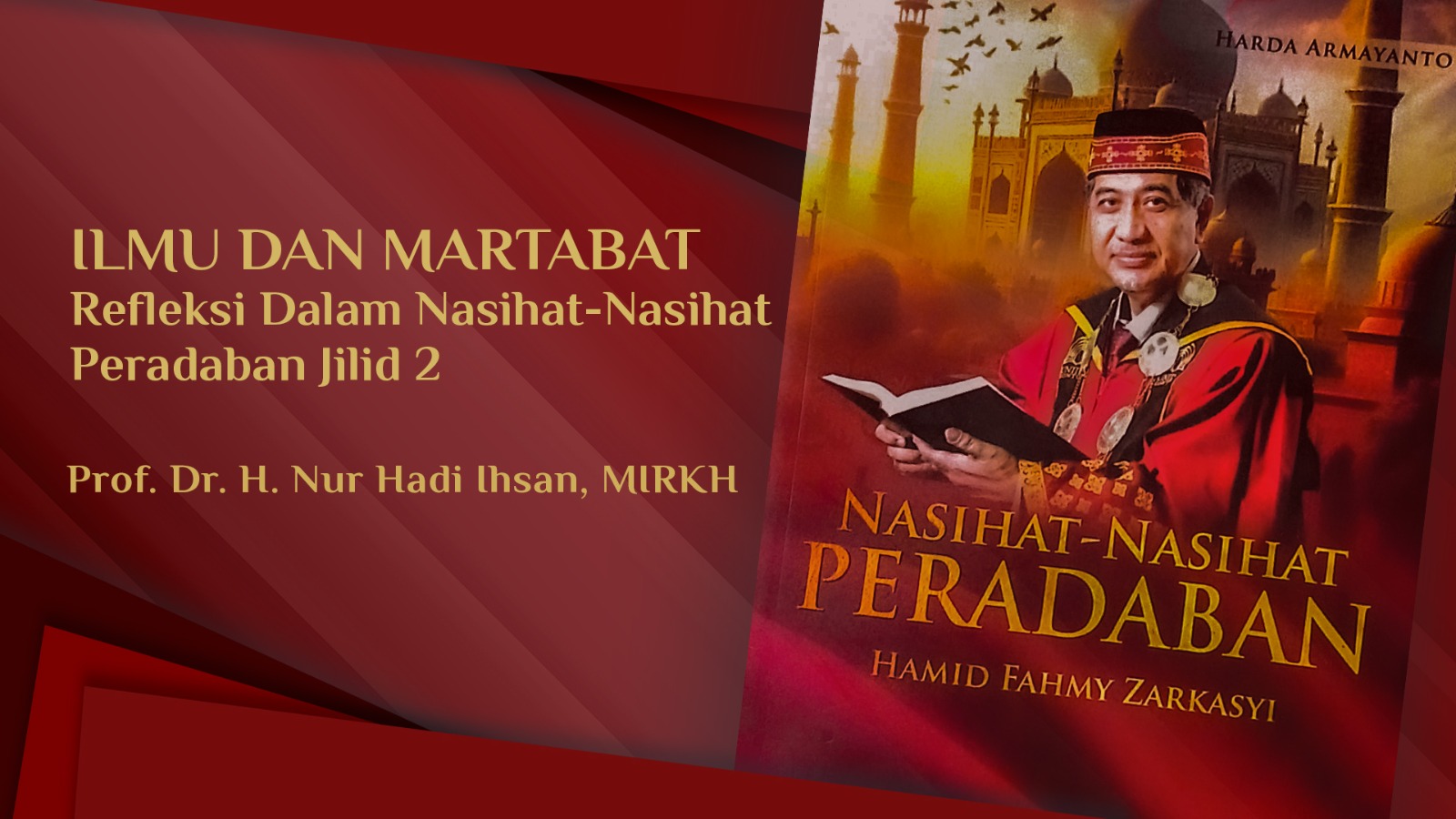Oleh: Prof. Dr. H. Nur Hadi Ihsan, MIRKH
“Jadilah manusia yang berkualitas secara ilmu dan akhlak.”
— Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.
Dalam tradisi Islam, kualitas manusia tidak pernah diukur dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari ilmu yang menerangi dan akhlak yang memuliakan. Ilmu membentuk akal, dan akhlak membentuk jiwa. Bila keduanya terhimpun, lahirlah manusia bermartabat—insān kāmil yang menjadi cermin cahaya Tuhan di muka bumi.
Kutipan dari Prof. Hamid di atas mengingatkan kita bahwa peningkatan kualitas manusia tidak mungkin dicapai hanya dengan mengumpulkan pengetahuan teknis. Ilmu tanpa akhlak adalah seperti pedang di tangan anak kecil—lebih banyak melukai daripada melindungi. Sebaliknya, akhlak tanpa ilmu membuat seseorang mudah disesatkan oleh emosi dan prasangka.
Ibn Sina menegaskan bahwa kesempurnaan manusia terbentuk ketika akalnya tercerahkan dan jiwanya tersucikan. Al-Ghazali kemudian menegaskan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang melahirkan khashyah—ketundukan hati kepada Allah. Tanpa takut kepada Allah, pengetahuan hanyalah beban intelektual yang memperberat hisab.
Ilmu yang Menumbuhkan
Di tengah gempuran modernitas, ilmu sering direduksi menjadi sekadar alat produksi atau instrumen ekonomi. Sains diposisikan sebagai dewa baru, sementara etika dan spiritualitas dibuang dari ruang peradaban. Inilah pola pikir Barat sekuler yang mengagungkan metode, statistik, dan objektivitas, tetapi melupakan manusia yang memegang alat itu.
Padahal, dalam worldview Islam, ilmu bukan sekadar “apa” yang diketahui, melainkan “bagaimana” pengetahuan itu mengubah manusia. Ibn Taimiyyah menyebut ilmu yang bermanfaat sebagai “ilmu yang menuntun kepada amal dan mendekatkan kepada Allah.” Ibn al-Qayyim menambahkan bahwa “ilmu harus menghidupkan hati sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang gersang.”
Oleh karena itu, pengetahuan yang hanya melahirkan kesombongan intelektual adalah pengetahuan yang gagal. Ia tidak mengangkat derajat manusia, malah menenggelamkannya dalam kabut ego. Modernitas melahirkan manusia pintar tetapi gelisah; berinformasi tetapi kehilangan makna. Itulah akibat ilmu yang kehilangan ruh.
Akhlak Sebagai Penjaga
Martabat manusia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi gelar akademiknya, tetapi seberapa bersih perilakunya. Akhlak adalah penjaga ilmu. Tanpanya, seseorang dapat menyebarkan kerusakan dengan dalih objektivitas ilmiah.
Ibn Khaldun menyebut akhlak sebagai “jiwa peradaban.” Bila ia baik, masyarakat berkembang. Bila ia rusak, bangsa runtuh sekalipun memiliki teknologi yang tinggi. Malik Bennabi, dalam analisis sosialnya, menunjukkan bahwa kebangkitan umat tidak dapat terjadi tanpa revolusi moral—revolusi akhlak yang menata cara berpikir dan bertindak.
Adapun tasawuf, dalam dimensi terdalamnya, tidak pernah memisahkan ilmu dari akhlak. Ia mengajarkan bahwa orang berilmu sejati adalah yang paling jujur, paling rendah hati, dan paling halus budi pekertinya. Abu al-Hasan al-Asy‘ari menegaskan bahwa keyakinan yang benar harus tercermin dalam amal yang benar. Di sinilah akhlak berfungsi sebagai bukti dari kemuliaan ilmu.
Benturan Dua Dunia
Di dunia Barat, kualitas manusia diukur dari kemampuan teknis, efisiensi kerja, dan produktivitas ekonomi. Manusia diperlakukan sebagai komoditas tenaga, bukan makhluk ruhani. Pandangan hidup sekuler memisahkan etika dari ilmu, dan memisahkan ilmu dari tujuan akhir keberadaan manusia.
Berbeda dengan itu, worldview Islam melihat manusia sebagai kesatuan—jasmani, akli, dan ruhani. Tidak ada pemisahan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran moral. Ibn Rusyd menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari sumber yang sama.
Sayyid Qutb dalam Ma‘ālim fī al-Tharīq menyatakan bahwa peradaban Barat melahirkan manusia yang “tahu banyak hal, tetapi tidak tahu untuk apa ia hidup.” Sementara Islam menciptakan manusia yang mengetahui posisi dirinya sebagai hamba dan khalifah. Ilmu tanpa kesadaran ini akan menghancurkan, bukan membangun.
Menata Keluarga Ilmu
Kualitas ilmu dan akhlak tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dalam ekosistem yang sehat—dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga komunitas intelektual. Prof. Hamid sering menegaskan bahwa peradaban Islam lahir dari komunitas berilmu yang saling menguatkan. Di masa keemasan Islam, ilmuwan tidak bekerja sendiri; mereka berada dalam milieu ilmiah yang menghidupkan dialog, membaca, menulis, dan memperbaiki diri.
Al-Faruqi menyebut bahwa peradaban Islam dibangun oleh tiga pilar: tauhid sebagai asas, ilmu sebagai alat, dan akhlak sebagai buah. Lembaga pendidikan—dari madrasah hingga universitas—harus mengembalikan peran utamanya: mencetak manusia beradab, bukan sekadar tenaga kerja.
Karena itu, krisis pendidikan hari ini bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena rapuhnya orientasi. Banyak lembaga pintar mengajar, tetapi gagal mendidik. Mereka mencetak orang cerdas, tetapi tidak melahirkan manusia mulia.
Menuju Manusia Bermartabat
Menjadi manusia berkualitas tidak cukup hanya dengan membaca banyak buku atau memiliki banyak gelar. Martabat terbentuk dari istiqamah dalam belajar, kesadaran diri untuk terus memperbaiki akhlak, dan kerendahan hati dalam menerima kebenaran.
Islam menuntut keseimbangan: ilmu yang benar melahirkan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia membuka pintu bagi ilmu yang lebih dalam. Di situlah martabat manusia tumbuh: dari kesungguhan mengasah akal dan kejujuran memelihara hati.
Penutup: Jalan Keheningan
Pada akhirnya, perjalanan ilmu adalah perjalanan kembali kepada keheningan hati. Di titik itulah manusia menyadari bahwa segala kecerdasannya tidak berarti tanpa budi pekerti, dan seluruh pengetahuannya tidak akan menyelamatkan tanpa ketundukan kepada Allah.
Jika kualitas manusia ditentukan oleh ilmu dan akhlaknya, maka setiap langkah kita harus diarahkan untuk memperbaiki keduanya. Ilmu menuntun langkah, akhlak menguatkan jiwa.
Semoga kita menjadi manusia yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga beradab; tidak hanya cerdas, tetapi juga lembut; tidak hanya memahami dunia, tetapi juga memahami diri sendiri.
Sebab martabat sejati bukan dipuji oleh manusia, tetapi diterima oleh Allah. Hanya dengan itulah hidup memperoleh maknanya yang paling dalam.
Mantingan, 6 Januari 2026
Prof. Dr. H. Nur Hadi Ihsan, MIRKH